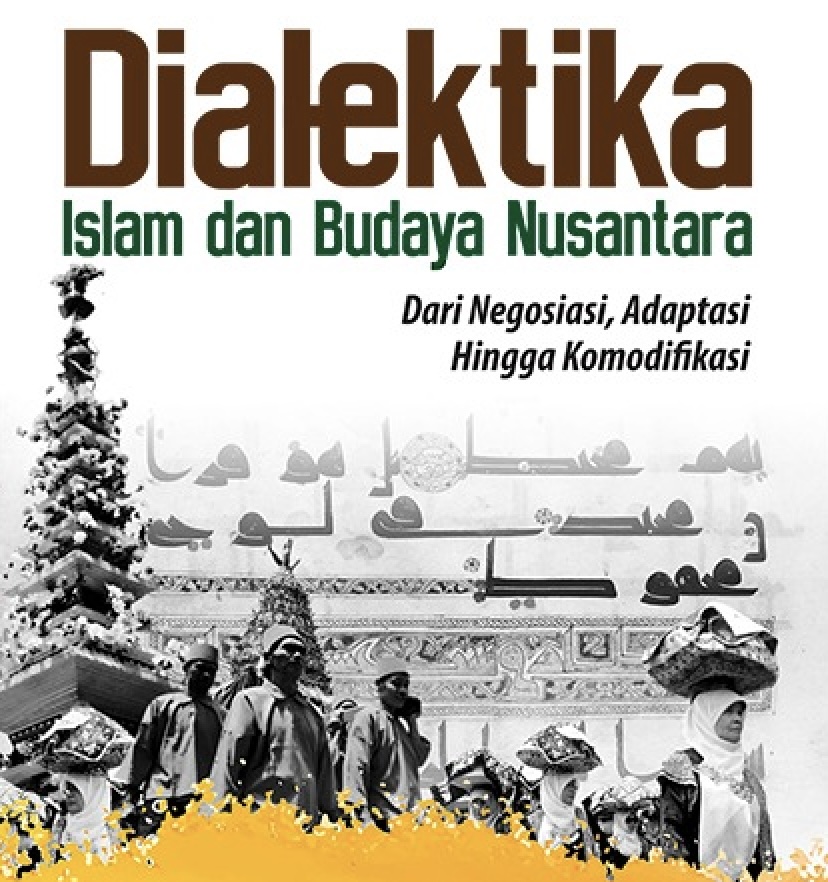Di tengah gempuran modernisasi dan arus globalisasi, desa seharusnya menjadi titik tolak kebangkitan bangsa Indonesia. Desa bukanlah sekadar unit administratif atau objek pembangunan, melainkan fondasi utama tempat identitas bangsa ditanam dan diwariskan lintas generasi. Sayangnya, selama berabad-abad, desa-desa di Indonesia justru dikerdilkan perannya hingga hanya menjadi penonton di panggung pembangunan nasional. Akar budaya desa tercerabut, ekonominya terpinggirkan, dan jati dirinya terasing di tanahnya sendiri. Di titik inilah konsep Panglima Desa hadir bukan sebagai simbol kosong, melainkan sebagai agen strategis dalam membangkitkan kekuatan bangsa dari akar rumput.
Dampak kolonialisasi terhadap Indonesia tidak hanya dalam penguasaan fisik wilayah, tetapi lebih jauh telah mencabut akar sejarah dan identitas bangsa ini. Sejarah Indonesia selama masa kolonial ditulis dari perspektif penjajah, di mana kerajaan-kerajaan besar Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Kesultanan Islam direduksi sebagai entitas lokal yang primitif. Budaya lokal dipreteli menjadi sekadar upacara dan seni pertunjukan tanpa nilai strategis sosial atau politik. Bahkan, nilai-nilai Islam sebagai kekuatan sosial masyarakat desa pun direduksi hanya pada aspek ritual dan simbol, menjauh dari perannya sebagai sistem nilai dan tata kelola sosial. Desa sebagai pusat produksi nilai dan kekuasaan pun tercerabut, digantikan oleh sistem birokrasi kolonial yang sekadar menjadikan desa sebagai hinterland ekonomi.
Padahal di balik kerusakan identitas ini, Indonesia menyimpan dua kekuatan besar: warisan budaya Nusantara dan nilai peradaban Islam. Budaya Nusantara dengan filosofi gotong royong, musyawarah, seni, bahasa daerah, dan tradisi agraris maritim telah lama menjadi kekuatan lokal desa-desa di seluruh pelosok negeri. Di sisi lain, nilai-nilai peradaban Islam seperti tauhid, keadilan sosial, persaudaraan (ukhuwah), serta sistem sosial syariah telah membaur dan hidup dalam praktik sosial masyarakat desa. Sayangnya, kedua kekuatan ini belum pernah benar-benar disatukan dalam satu desain besar kebudayaan bangsa. Di sinilah pentingnya peran strategis Panglima Desa, yaitu sebagai pemimpin transformasi sosial yang menyatukan budaya lokal dan nilai Islam sebagai fondasi kebangkitan Indonesia dari akar desa.
Kebangkitan desa harus dimulai dari revitalisasi desa sebagai pusat peradaban. Desa harus ditempatkan kembali sebagai pusat produksi nilai budaya, pusat solidaritas sosial, dan pusat ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Simbol budaya lokal harus dihidupkan kembali, bukan hanya sebagai ornamen upacara, tapi sebagai instrumen komunikasi dan identitas nasional. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong harus dimaknai ulang dalam bingkai nilai tauhid sebagai ibadah sosial, bukan sekadar tradisi nenek moyang.
Dalam proses membangun kekuatan desa, program seperti Ekspedisi Tempeh dan Ekspedisi Tenun dapat dijadikan model strategis untuk pemetaan kekayaan identitas desa. Ekspedisi-ekspedisi tematik ini berfungsi merekam teknik produksi tradisional, memetakan warisan budaya, hingga mendokumentasikan nilai filosofis yang terkandung dalam setiap produk khas desa. Hasil eksplorasi ini bukan hanya menjadi data budaya, melainkan dikemas menjadi produk industri kreatif, konten pendidikan, bahkan instrumen diplomasi budaya Indonesia di kancah global. Melalui dokumentasi digital, publikasi atlas budaya, festival budaya tahunan, dan materi pendidikan di sekolah, ekspedisi semacam ini menjadi gerakan strategis merekonstruksi identitas bangsa dari desa-desa.
Tidak berhenti pada pemetaan budaya, integrasi budaya lokal dengan nilai Islam juga menjadi syarat mutlak dalam pembangunan desa modern. Sistem pendidikan di desa harus memadukan pengajaran sejarah lokal, warisan leluhur, nilai-nilai adat, dan nilai-nilai peradaban Islam secara integratif. Sekolah dan madrasah di desa harus menjadi pusat pewarisan identitas, bukan sekadar tempat belajar akademik. Di sektor ekonomi, sistem koperasi desa berbasis syariah, pengelolaan wakaf produktif, dan pasar halal di tingkat desa dapat dikembangkan untuk membangun ekonomi riil masyarakat berbasis tradisi dan syariat. Budaya gotong royong yang diwarisi leluhur bisa diaktualisasikan sebagai energi kolektif dalam membangun usaha produktif di tingkat komunitas.
Untuk memperkuat jangkauan pengaruh desa, dokumentasi budaya dan ekonomi kreatif desa harus diangkat melalui media sosial, platform digital, hingga festival internasional. Desa-desa Indonesia harus tampil sebagai pusat peradaban global baru: desa digital yang tetap berakar kuat pada nilai tradisi dan peradaban Islam.
Di sinilah sosok Panglima Desa mendapat peran strategis. Panglima Desa adalah pemimpin transformatif, yang bertindak sebagai arsitek sosial dan kultural. Ia bukan hanya kepala administratif, tetapi pemimpin yang merekonstruksi sejarah, menghidupkan kembali nilai adat dan Islam, membangun ekonomi komunitas, dan memimpin diplomasi budaya desa di tingkat nasional maupun internasional. Panglima Desa harus menjadi insinyur sosial, penggerak komunitas, sekaligus duta identitas bangsa di era baru.
Bangkitnya Indonesia adalah kebangkitan desa. Desa yang kuat adalah desa yang mampu memahami dan menghidupkan warisan budayanya, membumikan nilai-nilai peradaban Islam dalam sistem sosial dan ekonominya, serta menjadikan dirinya produsen nilai dan budaya di kancah global. Program revitalisasi desa, ekspedisi budaya, industri kreatif desa, pendidikan identitas, dan diplomasi budaya harus menjadi satu kesatuan strategi dalam kebijakan nasional.
Membangkitkan Indonesia tidak cukup dari pusat. Indonesia harus dibangun dari desa. Dari warisan leluhur, dari nilai tauhid, dari produk ekonomi rakyat, dan dari solidaritas komunitas akar rumput. Desa adalah peradaban. Dan Panglima Desa adalah arsitek kebangkitan bangsa.
Sebagaimana ungkapan klasik:
“Bangsa yang kehilangan desanya, adalah bangsa yang kehilangan dirinya.”
Kini saatnya, dari desa, Nusantara bangkit kembali.