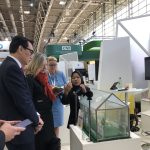Di sebuah sudut Indonesia, tepatnya di Desa Lembanna, Sulawesi Selatan, cahaya matahari tidak lagi hanya sekadar penerang siang hari, melainkan telah menjadi sumber kehidupan baru. Ibu Sartika, seorang warga setempat, kini dapat tersenyum lega melihat panel surya di atap balai desanya yang tidak hanya menerangi rumahnya di malam hari, tetapi juga menggerakkan mesin pengolah kopi yang menjadi tulang punggung perekonomian warga. Kisah sukses Lembanna ini bukanlah cerita isolasi, melainkan bagian dari gerakan besar yang melibatkan 1.200 desa lainnya di Indonesia yang telah bertransformasi menjadi “desa energi”, menjadi bukti nyata bahwa transisi energi justru dimulai dari akar rumput.
Data terkini dari Kementerian Desa PDTT tahun 2024 mengungkap potensi luar biasa yang selama ini terpendam, di mana 45% dari total 74.961 desa di Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang belum tergarap optimal. Mulai dari aliran sungai di desa-desa pegunungan yang cocok untuk mikrohidro, limbah pertanian di wilayah agraris yang dapat diolah menjadi biomassa, hingga gelombang laut di wilayah pesisir yang menyimpan energi tak terbatas. Realitas inilah yang mendorong pemerintah untuk menempatkan desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pelaku utama dalam peta jalan transisi energi nasional menuju 2045.
Beberapa desa telah menjadi pelopor dengan kisah sukses yang menginspirasi, seperti Desa Tenganan di Bali yang berhasil mencapai kemandirian energi 100% melalui sistem hybrid surya dan mikrohidro, bahkan mampu mengekspor kelebihan listrik ke desa tetangga. Sementara itu, Desa Banyuwangi di Lombok mengembangkan biogas dari kotoran sapi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi desa, tetapi juga menghasilkan pupuk organik berkualitas. Tidak ketinggalan Desa Kete Kesu di Toraja yang memanfaatkan limbah kopi menjadi sumber energi biomassa inovatif.
Menyikapi potensi besar ini, pemerintah meluncurkan tiga program utama yang menyentuh langsung ke akar rumput, dimulai dengan program Desa Mandiri Energi yang menargetkan 10.000 desa pada 2030 dengan anggaran Rp 20 triliun, dilanjutkan dengan Solar Village Initiative yang menyediakan instalasi panel surya atap dengan subsidi 75% untuk desa tertinggal, serta Energy Literacy Movement yang fokus pada pelatihan teknisi energi terbarukan untuk pemuda desa. Namun, perjalanan menuju transisi energi desa tidak selalu mulus, berbagai tantangan nyata masih menghadang di lapangan, mulai dari biaya awal instalasi yang tinggi, keterbatasan teknisi lokal, kerumitan perizinan, hingga masalah pemeliharaan pasca-instalasi yang seringkali membuat banyak proyek mangkrak di tengah jalan.
Berbagai solusi inovatif berbasis kearifan lokal pun bermunculan untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti sistem bagi hasil energi dimana warga menyewakan atap untuk panel surya dan mendapat bagi hasil listrik, pembentukan koperasi energi desa yang mengelola energi secara kolektif, serta pengembangan teknologi tepat guna yang mudah dioperasikan dan diperbaiki oleh masyarakat setempat. Dampak nyata dari transisi energi desa ini ternyata bersifat multidimensional, tidak hanya dirasakan secara ekonomi melalui penghematan biaya energi 40-60% dan terciptanya usaha baru berbasis energi, tetapi juga secara sosial melalui pengurangan urbanisasi dan pemberdayaan perempuan melalui UMKM energi, serta secara lingkungan melalui penurunan emisi karbon dan pengurangan ketergantungan bahan bakar fosil.
Peran generasi muda desa menjadi kunci kesuksesan gerakan ini, seperti yang ditunjukkan oleh Ahmad, seorang pemuda 25 tahun lulusan SMA yang berhasil menjadi teknisi surya di desanya dengan penghasilan Rp 5-7 juta per bulan, membuktikan bahwa merantau bukan lagi satu-satunya pilihan untuk mencapai kesejahteraan. Peta jalan menuju 2045 pun telah disiapkan dengan target yang jelas, dimulai dengan 5.000 desa mandiri energi pada 2025, 20.000 desa dengan akses energi bersih pada 2030, hingga seluruh desa di Indonesia menggunakan energi terbarukan pada 2045. Kemitraan strategis dengan berbagai pihak meliputi swasta melalui program CSR, universitas dengan pendampingan teknologi, LSM untuk pemberdayaan masyarakat, dan komunitas dalam pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penentu keberhasilan agenda besar ini.
Di balik semua data dan program, yang paling penting adalah cerita harapan yang terpancar dari desa-desa seperti Lembanna, dimana anak-anak kini dapat belajar dengan penerangan yang stabil, ibu-ibu tidak lagi menghirup asap beracun dari kayu bakar, dan warga tidak perlu merantau meninggalkan keluarga untuk mencari pekerjaan. Transisi energi desa mengajarkan pelajaran berharga bahwa teknologi harus sesuai dengan konteks lokal, masyarakat harus menjadi pemilik proses, dan keberlanjutan jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan implementasi. Saat matahari terbenam di Lembanna, panel-panel surya masih setia menangkap sinar terakhir untuk disimpan dalam baterai, bagaikan harapan untuk desa-desa Indonesia yang terus menyala—terang, bersih, dan berkelanjutan. Tahun 2045 mungkin masih terasa jauh, tetapi di desa-desa Indonesia, masa depan yang lebih baik sudah dimulai hari ini, dibangun dari pinggiran dengan semangat gotong royong, satu panel surya, satu turbin mikrohidro, dan satu biogas dalam sekali waktu.